Akhirnya Lagu itu Jadi Lagu "Favorit" Kita Semua, Tapi Kok Berasa Bukan Kita yang Milih Ya?
Lo pasti sering dong dengar sebuah atau beberapa lagu tertentu diputar secara intens di radio, mal, kafe, IG, TikTok, bahkan di angkot. Tapi lo pernah kepikiran gak: pemutaran lagu terpilih itu idenya siapa sih sebenernya? Siapa yang milihin? Pilihan publik... atau pilihan siapa?
Pernah gak kita denger lagu yang dari segi tema, lirik, musik, bahkan vibe-nya tuh menurut kita ya... b aja? Tapi entah kenapa ya, kok lagu itu kedengeran mulu saban pagi, siang, sore, dan malam. Diputar di mana-mana: di radio, kafe, kantin sekolah, barbershop, sampe di warung ayam geprek kesukaan kita.
Pernahkah kita bertanya kenapa bisa begitu?
Yap. Kita hidup di abad dimana selera publik bisa dibentuk, kesukaan bisa diarahkan. Apa-apa yang 'naik daun' atau viral seringkali tidak selalu terangkat melalui proses yang natural dan organik.
Yap. Kita hidup di zaman yang serba lucu campur ngeselin. Zaman dimana pilihan pemutaran lagupun bisa diarahkan, dipesan atau dibeli, ranking chart bisa dimanipulasi, slot manggung bisa dibuat "aman terkendali". Lo pikir lo nikmatin lagu karena selera lo? Hihihi, nggak, Bro. Seringnya, lo lagi dicekokin, ya kan? Dan di tengah semua itu, kita para pendengar, penikmat, bahkan juga pelaku musik sendiri, tanpa sadar sudah menjadi “korban” dari kebangetan-kebangetan yang "nggak banget" ini.
Politik Suara: Siapa yang Nentuin "Playlist" Kita?
Pernah gak lo ngerasa sebel waktu nyetel radio eh tau-tau lagu yang diputar itu lagi, itu lagi? Terus lo mikir: “Apakah ini selera masyarakat? Atau ini playlist yang dibentuk sama yang punya kuasa menentukannya, memutarkannya?”
Yeah ... Selamat datang di ranah yang kita sebut politik suara. Dan salah satu praktik paling "suek" di dalamnya adalah: Payola. Ya, dialah Miss Payola.
Payola bukan adiknya Pay Later ya, walaupun sama-sama terkait urusan bayar-membayar. Payola adalah nama halus dari praktik kotor ilegal: memberi sogokan kepada suatu pihak yang memiliki "kuasa publikasi" agar suatu lagu bisa sering diperdengarkan ke telinga publik via fasilitas media publikasi massa. Dalam kacamata hukum hal tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi gelap: tindakan suap-menyuap. Sogokan bernama 'Payola' bisa beda banget dengan paid promote, tapi bisa juga beda tipis. Nanti kita akan cermati dan buktikan lebih lanjut.
Lah, Apa Urusannya Sama Kita?
Ketika industri musik dimanipulasi dari belakang layar oleh duit dan kuasa, maka yang kita dengar sesungguhnya bukanlah lagu atau realitas musik melainkan suara hasil editan kekuasaan: uang. Dan ini gak cuma soal musik. Ini soal nilai-nilai kehidupan. Ini tentang kita semua. Kecuali kalau kita memang nggak peduli (atau malah mendukung) korupsi, kolusi dan nepotisme, ya gak akan terasa bahwa hal ini tuh sebenarnya sudah di level genting: liar tak terkendali.
Dan kalau sekarang kita ngebahas Payola, bukan berarti kita benci musisi sukses. Bukan juga karena iri sama yang lagunya booming. Bukan dengki sama rezeki orang lain. Bukan hendak memusuhi musisi atau menjatuhkan teman-teman yang berkhidmat di ranah media dan publikasi. Bukan juga hendak bilang "naik daunin gue dong", sori yee karya-karya gue (dan band gue) udah lumayan banyak yang muter atau nonton secara organik, dan beberapa juga sempat masuk playlist resmi DSP, murni natural-organik tanpa "main belakang" 😘. Gue nulis ini karena ada yang jauh lebih penting dari itu semua: kebenaran, keadilan, kejujuran.
So, udah jelas kan? Payola bukanlah masalah sepele, dia udah jadi salah satu penyakit sistemik stadium lanjut di kehidupan kita.
Yuk Mari Kita Lebih Dekat dengan "Neng Payola"
Payola = praktik membayar (secara terang-terangan atau terselubung dengan melanggar batas SOP) kepada awak radio, TV, program musik, meja redaksi, majalah, channel video, platform streaming atau berbagai ragam media publikasi lainnya agar lagu tertentu diputar, dipromosikan, atau dimasukkan ke dalam playlist. Bukan karena lagunya bagus atau enak, bukan dan belum tentu begitu, Bray. Tapi karena ada duit di baliknya: insentif gelap. Intinya 'nyogok biar lagunya diputarin terus, lebih diprioritaskan dibandingkan lagu-lagu lain. Diperlakukan istimewa.
Sejarah Singkat: Biografi "Miss Payola"
Istilah Payola mulai viral di Amerika Serikat era 1950-an. Diambil dari pay for play, pay for Vitrola, diasosiasikan ke sebuah merk radio lawas legendaris. Waktu itu radio jadi medium siar utama buat musik populer, dan praktik “bayar agar lagu diputar” waktu itu marak banget. Puncak skandal besar-besaran Payola terjadi pada tahun 1959-60an. Penyiar kondang, Alan Freed (bapaknya rock and roll), dikenakan tuduhan menerima sogokan dari sebuah label raksasa agar lagu-lagu tertentu diputar lebih sering.
Hasilnya, Alan Freed dipecat. Industri musik diguncang. Tapi... praktik Payola-nya? Yes, tetep aja jalan. Cuma makin rapih. Makin diam-diam. Makin seru, saru, samar, dan tampak seolah-olah "elegan".
Payola Versi Indonesia? Jauh Lebih Kreatif
Praktik payola bukan cuma terjadi di radio. Ranah TV, mal, platform streaming, bahkan ruang publik semacam terminal, angkutan umum, restoran, kafe juga bisa dijadikan ruang beroperasinya Payola. Dan tentu ini adalah sebentuk kerjasama gelap nan tak beradab antara berbagai pihak terkait musik: musisi, manajemen artis, label, media, promotor, dlk. Semua dibuat kelihatan tampak “organik”, padahal promosi penuh kepalsuan.
Di Indonesia aksi sogok menyogok bisa berbentuk sangat halus, amat ramah nan manis penuh kehangatan dan kekeluargaan, berupa: traktiran, ajak jalan-jalan, kiriman bingkisan atau barang berharga, bahkan sodoran "daging empuk". Kebusukan yang menyamar sebagai 'keramahan budaya'.
Jadi, Payola itu suap ya? Ya iyalah karena memanipulasi bahkan membajak sistem publikasi (siaran/media informasi), dan jelas-jelas menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Ada 'jalan umum' atau sistem netral yang terganggu.
Meski dalam praktiknya, pelakunya bisa saja bilang: “Ah itu kan cuma (biaya) promosi.” “Lagian, semua juga ngelakuin itu kok...”. Dan di sinilah kerusakan hebat itu terjadi. Karena semua orang menganggapnya 'biasa aja', karena semuanya menganggapnya wajar. Padahal? Skandal busuk.
Kita gak bilang promosi itu haram. Kita juga gak hendak nyalahin semua pihak yang muterin lagu karena memang dia sah dan resmi dibayar untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kita bicarakan dan permasalahkan di sini adalah: (oknum perusak) keadilan dalam informasi publik, kesetaraan untuk 'mendengar' dan 'didengar'. Semua karya musisi berhak untuk 'diperdengarkan' ke telinga publik. Publik berhak untuk mendengar beragam karya musik, bahkan berhak juga memilih dan menentukan mana yang mereka anggap terbaik. Tapi kalau yang diperdengarkan oleh oknum media publikasi dan terus dicekokkan oleh oknum platform streaming adalah yang bisa bayar paling mahal? Apakah itu fair dan adil? Nah lo.
Pusing gue, masa promosi = suap Payola?
Paid promote bisa jadi payola ... tapi gak semua paid promote itu payola. Kira kira begini, Bro ... Paid promote tuh kayak lo minta pendapat orang tentang diri lo, lo bayar dia buat jasa ngereview dengan jujur. Sementara Payola tuh kayak lo bayar dia buat pura-pura suka, nyuruh dia buat bilang yang manis-manisnya aja, mesen dia buat cakep-cakepin lo. Paid promote tuh lo ikutin lampu merah, bayar pajak, pake helm. Payola tuh lo gaskeun naik trotoar biar bisa nyalip kemacetan. Paid promote tuh toko lo muncul di Google Maps via iklan resmi. Payola tuh lo bayar hacker biar toko kompetitor ilang dari peta. Paid promote itu kayak lo daftar lomba, bayar biaya pendaftaran. Payola itu lo bayar panitia biar nilai lo dinaikin diam-diam.
Dan lo tau apa yang gak kalah berbahayanya dari Payola? Ketika publik (bahkan kalangan musisi) nggak ngeh sama hal ini, sudah gak peduli lagi, dan menganggap yang begitu-begitu sebagai 'udah kodrat alamiahnya dunia bisnis atau industri musik'. Padahal, Payola adalah jalan lurus menuju praktik setan bernama monopoli. Jelas melabrak etika dagang, norma usaha, dan tentu saja melawan hukum. Ia jelas-jelas jauh dari nafas ekonomi Pancasila.
Promosi Musik: Iklan Fair vs Iklan Jahat
"Hari gini lagu tuh nggak usah bagus-bagus amat, yang penting budget promosinya gila-gilaan."
Kalimat di atas mungkin terasa kasar, bahkan ofensif bagi sebagian musisi "idealis". Tapi inilah realita yang tak bisa diabaikan dalam kegiatan industri musik. Fasilitas promosi musik kini bukan lagi sekadar alat bantu penyebaran karya, tapi sudah bagaikan sosok sakti yang bisa menentukan lagu apa/siapa yang "ada di mana-mana" dan lagu apa/siapa yang "nggak nongol sama sekali." Tidak semua bentuk promosi itu jahat. Mari kita tegaskan bedanya mana promosi (push, boost, ads) yang wajar, mana yang sebaliknya: jahat.
Promosi yang fair dan sehat adalah promosi sesuai SOP yang seringkali muncul sebagai dampak atau hasil dari: apresiasi jujur-organik dari publik terhadap suatu karya, kesadaran kolektif yang organik dari publik atas kualitas atau keunikan sebuah karya, juga kesadaran obyektif promosional dari stakeholder musik bahwa karya tersebut memang layak dan pantas untuk lebih disebarluaskan. Dengan syarat: ikuti SOP, tidak kalap "bakar uang" secara membabi-buta, tidak mengarah ke monopoli, baik halus maupun kasar. Etis.
Sedangkan promosi yang jahat adalah promosi yang: memaksakan opini, berusaha me-monopoli pasar dengan cara memanipulasi selera publik melalui bombardir iklan tanpa jeda, menyisipkan dan menyusupkan musik with Payola ke berbagai ruang publikasi tanpa memperhatikan apakah orang suka atau tidak, terima atau tidak, mengabaikan kualitas karya demi kepentingan branding atau target pasar. Sederhananya, ini bukan soal “promosi/iklan itu baik atau buruk”, tapi soal niat, cara, dan dampaknya.
Gak masalah sih kalo niatnya memperluas distribusi produk. Tapi ya jadi kacau kalau semua itu diatur berdasarkan kuasa uang, bukan kualitas atau relevansi karya. Dan yang tak kalah gawat lagi >> Ada banyak loh musisi yang begitu. Di sisi lain masih ada juga musisi yang tengah bersusah payah berproduksi dan berpromosi dengan jujur, penuh keringat, darah dan air mata — tapi gak punya modal gede buat promo, plus nggak punya koneksi ke media sebagai corong ruang informasi publik. Mereka tetap teguh dalam prinsip, terus bertahan dengan sikap dan cara-cara mulia. Hasilnya? We already know kan.
Soal kualitas karya, bagaimana suatu karya disebut layak? Bagaimana mekanisme penentuannya? Siapa yang berhak menentukan?
Tema "pengkurasian/penjurian/editorial/kuratorial" musik akan kita bahas tuntas pada tulisan terpisah setelah ini.
Solusinya? Edukasi Selera & Etika Promosi
Ini bukan hanya soal mengkritisi sistem. Ini soal membangun kesadaran bahwa musisi dan timnya harus lebih punya kesadaran dan tanggung jawab artistik dan sosial, dan tentu saja tanggung jawab moral. Bahwa talent, talent management, promotor, label, dan penyedia platform perlu suportif dan sportif memperhatikan fairness. Bahwa pendengar pun perlu belajar membedakan mana musik yang menyentuh karena jujur, dan mana yang nempel di kuping dan rongga kepala karena dijejelin sama algoritma uang: duitgoritma.
“Jangan cuma nanya: ‘Oh, ini lagi viral?’, tapi tanya juga: ‘Ini layak viral karena apanya ya?’” Kalau naik daun karena banyak review yang bilang gitu, coba pertanyakan lagi deh, apakah review-review tersebut obyektif dan jujur? Pertanyakan terus! Kejar terus!
Kalau musik dipromo-iklankan dengan jujur dan etis, semua akan mendapat manfaat: musisi berkembang karena karyanya diapresiasi, pendengar punya pengalaman mendalam, dan industri tumbuh dengan sehat. Tapi kalau pelaku industri musik tetap lebih percaya pada kekuatan modal promosi dibanding kekuatan lagu dan penyampai(annya), maka bersiaplah, kita sedang membangun industri sabun mandi atau junk food, bukan ekosistem musik. Payola, barangkali agak mirip dengan panic buying. Di mata hukum, etik dan moral, keduanya tentu sama bejatnya. Payola boleh juga kalau mau disebut: crazy paying.
Payola Masuk Ke Semua Ruang Publikasi
Ada musisi yang baru muncul tapi tiba-tiba udah diundang tampil di prime time TV? That’s not just exposure. That’s usually expenditure.
Digital Streaming Platforms (DSP), medsos musik, dll katanya sih "demokratis", lo upload lagu, lalu sistem akan bekerja otomatis berdasarkan kualitas karya, engagement, dan preferensi pendengar. Tapi... Coba deh lo pikir baik-baik: "Lagu siapa sih yang sering banget muncul di kolom rekomendasi lo meskipun lo sadar gak pernah nyari lagu itu?"
Itu karena dunia playlist DSP juga sudah jadi pasar berkabut gelap. Lo bisa “masuk” ke playlist populer, asal... ada dana besar yang nyokong. Ada ordal atau tim pitching yang punya “channel”. Atau budget promo yang siap jor-joran di-push di awal rilis. Dan ini bukan sekadar bayar, tapi bayar untuk "dilihat seperti tidak bayar" alias tidak tampak nyogok. Welcome to the world of duitgorithma. Di mana data dicocok-cocokkan dengan dana, grafik statistik dipoles biar kelihatan organik, lagu digenjot engagementnya via campaign fake account, bot streamers, comment bot, dan fake ads.
Lalu musisi mandiri? Dinasehati agar rajin-rajin share link lagu sendiri ke grup WA keluarga, WAG alumni sekolah anu, WAG RT/RW tempat tinggal, WAG komunitas kampus dll. Yang denger seringkali cuma puluhan orang, di antara mereka juga banyak yang belum paham betapa berharganya dukungan play, klik like, save atau favorite demi mensupport musisi mandiri modal dengkul. Musisi DIY mandiri seringkali "patah sebelum tumbuh".
Makanya kemudian mereka yang minim budget promosi akhirnya banyak juga yang bingung, linglung, bahkan frustasi, karena lagunya 'tak kunjung naik'. Lalu terdorong bisikan ifrit untuk menghalalkan segala cara: melakukan berbagai rekayasa manipulatif dan menggencarkan berbagai bentuk 'fake activity' demi menaikkan engagement, angka streams, views dll, dengan dalih "terpaksa begitu" karena tak ada jalan lain dan semua orang juga begitu. Padahal? Bukankah kelakuan palsu nan culas itu sama suek-nya dengan yang melakukan Payola?
Fake is new real
Dan akhirnya kita sebagai publik sedang dan terus dibentuk tanpa sadar agar selaras dengan agenda para peculas. Kita dipaksa percaya bahwa apa yang sering terdengar atau diperdengarkan di mana-mana = apa yang kita suka = itulah yang paling bagus. Kalau semua pilihan sudah disaring, ditentukan dan dikondisikan, itu mah bukan pilihan namanya melainkan penggiringan dan penjebakan.
Siapa yang Diuntungkan? Siapa yang Tersingkir?
Pelan-pelan di sini kita akan bongkar siapa yang memelihara kepalsuan-kepalsuan itu dan siapa yang tersingkir meski karyanya sebenarnya cukup layak, bahkan lebih layak dikenal dan dikenang.
BUDGET BERBICARA = LAGU PUN “BERPUTAR”
Payola dalam Industri Musik di Indonesia
"Bro, musisi nggak cuma butuh bakat, tapi juga kudu ada budget." Yes, bakat bisa jadi tiket masuk. Tapi dalam industri musik, yang bikin pintu studio, radio, hingga panggung live bisa terbuka lebar seringkali bukan cuma soal kualitas lagu dan bakat musisinya. Duit yang mengalir di balik layar tuh punya peran besar dalam menentukan lagu mana yang bakal naik, dan mana yang cuma bakal jadi kenangan di folder karya di hardisk laptop. Payola makin canggih dan terselubung di era digital.
"Jangan naif, Bro. Musik itu juga ekonomi." Iya, tapi bukan berarti menghalalkan segala macam cara kan?
Di Indonesia, cara dan bentuk payola bisa bermacam-macam: amplop ke penyiar atau produser acara, pembelian gila-gilaan slot airplay (paket mingguan/bulanan/tahunan), bayaran terselubung untuk bisa tampil di TV atau konser musik besar.
Payola Digital: Algoritma Juga Mungkin Banget Bisa Disogok
Di era DSP (Digital Streaming Platform), banyak orang percaya: kalau lagu lo bagus, nanti juga pasti akan naik sendiri kok. Sayangnya, realita tak semanis itu, Bro, Sis. Playlist editorial besar bisa "dipesan". Iklan pre-roll bisa dibeli agar lagu terlihat “rame”. Bot bisa dipakai untuk ngeboost angka. Dari situlah muncul istilah baru tadi: duitgorithma. Campuran antara uang dan algoritma.
Siapa yang sanggup bayar kampanye besar-besaran akan punya peluang lebih besar masuk dalam jangkauan radar DSP, yang pada akhirnya jadi lebih sering ditengok, didengar dan disukai oleh banyak orang, terlepas dari bagaimana kualitas musiknya.
Banyak orang berpikir algoritma itu netral. Tapi di baliknya ada pola-pola seleksi yang bisa dipengaruhi, bahkan dibayar/dimanipulasi. Playlist utama bukan lagi cerminan selera pendengar, tapi kadang kala merupakan hasil dari strategi kapital. Musik yang tak sesuai dengan “aroma algoritma” otomatis tersingkir, tak peduli seberapa tinggi kualitasnya. Sudah saatnya audiens dan musisi memahami logika ini, membongkarnya, dan tak tunduk takluk pasrah padanya.
Ruang Publik = Ruang Promosi Bayaran?
Di warung kopi, mal, food court, kampus, bahkan gym, playlist yang diputar tak selalu netral. Banyak yang sudah “dikurasi” berdasarkan paket langganan promosi dari pihak musisi, label, talent management, atau agensi publikasi. Bukan mustahil lagu yang lo dengerin di warung bakso itu, sebenarnya dibayar untuk nongol di situ, berkali-kali. Bahkan dalam acara kampus atau komunitas, ada loh “lagu sponsor” yang wajib diputar karena panitia kerja sama dengan brand tertentu. Kesemua contoh ini riil, nyata.
Lah Kalau Gitu, Apa Harus Ikutan "Main Kotor" Supaya Bisa Diputar atau Tampil?
Ini pertanyaan moral yang penting dan genting. Banyak musisi muda bertanya: "Apa harus bayar dulu supaya bisa diputar? Kenapa nggak kualitas aja sih yang bicara?" Jawaban jujurnya: ya dan tidak.
Ya, kalau emang lo mau masuk ke dalam dan menembus sistem industri arus utama, dan lo siap "bermain" di level permainan mereka. Bisa tetap “bersih” kok, Kan tetap ada jalur promosi yang wajar, sah dan panjang umurnya serta mulia: white marketing.
Tidak, kalau lo ingin membangun ekosistem sendiri, komunitas sendiri, dan jalur distribusi yang otentik dan organik. Tapi harus realistis: tanpa strategi ciamik dan resources memadai, karya bagus dan layak ngehits bisa tenggelam dalam banjir konten yang lebih viral dan lebih dibekingi duit gede.
Terus, Solusinya Apa?
Bikin ekosistem alternatif. Mau nggak mau, musisi dan komunitas harus cari jalur alternatif, kurasi kolektif, bikin playlist komunitas, bikin media independen (sst kayak gue sekarang ini, hehehe), sebar tulisan review karya dan wawancara talent tanpa bayaran, dirikan radio komunitas yang muterin lagu-lagu karena cinta, bukan karena amplop. Jalanin showcase dan tur kecil, bangun fanbase organik. Ini mungkin berjalan lambat. Tapi lebih jujur, lebih membangun fondasi jangka panjang, dan lebih terasa berjiwa dan sangat adil serta bijaksana. Terhormat.
Ingat: Duit Bisa Bikin Lagu Terdengar Di Mana-mana, Tapi Nggak Auto Bisa Bikin Lagu Dikenang
Payola bisa bikin lagu lo muter terus di mana-mana hari ini, tahun ini, tapi nggak menjamin akan diingat 10 atau 20 tahun lagi. Justru lagu-lagu yang menyentuh hati pendengar, meski tanpa modal promosi besar, seringkali bertahan lebih lama. Karena mereka hidup di ruang batin, bukan hanya di ruang komersial. Musik itu magis, Bro.
Jadi pilihannya, mau viral sesaat (baca: sesat 🤭), atau abadi dalam kenangan lintas generasi? The choices is yours.
Yang Diuntungkan? Yang Tersingkir?
Ini tentang ketimpangan antara yang "cuan" dan yang "boncos" di panggung industri musik. Di satu sisi, kita menyaksikan ada talent musik dengan sorotan lampu panggung, banjir streaming, dan eksposur tak berhenti-berhenti di medsos, TV, sampai headline media digital. Di sisi lain? Ada ribuan musisi mandiri/band independen yang mencipta dan memainkan karya jujur dengan kualitas setara atau 'berani diadu' tapi cuma disuruh sabar duduk di “kursi tunggu” di emperan algoritma.
Inilah dua sisi dunia dalam satu lanskap industri musik:
• Musisi dengan dukungan modal besar → dapat sorotan dan panggung
• Musisi mandiri DIY modal dengkul → dapat "ampun-ampunan"
Ketika cuan menentukan 'siapa yang didengar', musisi/band yang punya backing modal besar bukan cuma menang di ranah promosi, tapi mereka juga menang di persepsi. Budget promosi yang besar bisa “membentuk kenyataan”, dan membangun narasi bahwa "lagu ini keren, karena semua orang dengar". Padahal belum tentu ya kan?
Sementara itu, karya musisi DIY yang mandiri nan independen yang berkualitas dan penuh ketulusan kadang cuma numpang lewat di linimasa, sebelum akhirnya dikubur algoritma. Sebuah ironi tentang kualitas dalam hal estetika.
Sabotase Ruang-Ruang Media
Ruang yang berstatus “publik” kini makin dikuasai oleh kekuatan modal. Playlist radio, TV, bahkan playlist platform streaming konon katanya banyak yang sudah jadi arena penuh “penitipan” dan “penyelipan”. Ruang kantin, angkot, cafe, mall, bahkan FYP paltform anu—semua udah jadi ladang iklan terselubung. Lagu yang mestinya menyentuh karena makna, sekarang dipilih karena siapa yang lebih mampu 'membayar agar terdengar'. Yang diangkat dan diuntungkan selalu itu lagi itu lagi. Itu-Itu lagi. Pemain besar makin besar. Pemain kecil? We know deh.
Dan bahkan di skena yang katanya, ehem, "alternatif" pun, aroma ketimpangan tetap kentara kok. Indie ya nggak indie kalo "maenan duit".
So, pertanyaannya: apakah kejujuran, keragaman, dan kualitas masih punya tempat? Ataukah semua harus lewat gerbang dana promosi gila yang mengandung sogokan besar dulu baru bisa masuk telinga publik luas?
Kalau gitu, sebenarnya ini tentang “main musik” atau “main monopoli” sih?
Syukurlah masih ada banyak juga media publikasi dan awaknya yang terbilang fair, sportif, jujur, dan adil.
REFLEKSI SEDERHANA
Ini Bukan Kompetisi Kualitas Musik, Ini Kompetisi Dompet
Semua musisi butuh makan. Tapi bukan berarti semua musisi harus jadi pedagang ilusi. Yang berkarir musik via jalur mandiri jangan sampai tenggelam hanya karena tak punya cukup “amunisi promosi”.
Fenomena ini bukan sekadar soal uang. Ini soal keadilan estetika. Soal siapa yang berhak masuk ke ruang dengar publik. Tentang bagaimana musik seharusnya menjadi seni yang dipilih karena menggetarkan, bukan karena menggemukkan kantong. Kita perlu jujur bahwa selama budaya “amplopisme” ini masih dominan, maka musisi-musisi kecil akan tetap tenggelam, bukan karena mereka kurang cahaya, tapi karena cahayanya diselimuti kabut bernama sistem yang manipulatif, nepotis, kolusif dan koruptif.
Kita Udah Terlalu Biasa dengan Ketidakadilan
Di negeri ini, ketidakadilan bukan cuma sering terjadi, tapi juga seringkali dianggap wajar. Kita nyaris tak lagi terkejut saat melihat pelanggaran kecil atau bahkan besar terjadi di jalan raya, praktik sogokan di balik meja, atau sistem ribet yang pelik-rumitnya hanya berlaku buat yang nggak punya "orang dalam". Perlahan, ini semua menjadi kebiasaan. Kita pun jadi terbiasa. Payola, barangkali mirip sekali dengan istilah 'SIM tembak'. Ups.
Di dunia musik, penyakit sosial yang sama menjalar dengan cara yang lebih halus, tapi tak kalah mematikan. Yang punya modal besar bisa menempati etalase utama, bahkan jika tanpa kualitas musik yang benar-benar kuat sekalipun. Di negeri dimana tatanan sosial kemasyarakatannya sudah terlalu lama disetir uang dan koneksi, idealisme nyaris jadi bahan lelucon. Dan masalahnya, kejumudan tersebut bukan cuma ada dan terjadi di level pelaku kelas atas, tapi juga di level para penonton, pendengar, dan bahkan kita sendiri sebagai masyarakat umum di akar rumput.
Kita sudah terbiasa dengan yang palsu. Sudah terbiasa dengan lagu yang “dipaksakan jadi hits”. Sudah terbiasa melihat artis yang naik daun karena gimmick receh dan viral settingan, bukan karena karyanya wow dan berdampak luas. Jangan-jangan kita memang sedang mengalami krisis kecerdasan pendengaran: mendengarkan dengan hati nurani. Jangan-jangan kita sudah terlalu jauh hanyut dalam budaya “yang penting laku”, sampai lupa bertanya: apakah ini pantas naik? Apakah ini jujur? Apakah ini adil? Apakah kita masih peduli pada kejujuran dalam berkesenian? Berintegritas dalam ekonomi? Atau jangan-jangan kita memang lebih suka yang palsu, selama itu viral dan cuan?
Payola: Dosa Etika dan (Dugaan) Pelanggaran Hukum
Payola bukan sekadar praktik “bagi-bagi amplop” buat nyogok penyiar atau pengabar berita. Ia adalah wajah lain dari kolusi, korupsi, dan pembajakan atas kontrol terhadap ruang netral informasi publik, dan ia juga merupakan bentuk manis menawan dari perampasan hak masyarakat atas informasi dan keberagaman ekspresi seni musik. Payola punya dampak buruk struktural terhadap ekosistem bisnis dan budaya.
Dalam perspektif etika jurnalistik dan penyiaran, payola jelas melanggar prinsip integritas, independensi, dan transparansi. Ketika lagu-lagu diputar bukan karena kualitas artistik, tapi karena ada transfer uang atau hadiah di bawah meja, maka kepercayaan publik terhadap media akan ikut tergerus.
“Penyiaran bukan milik perusahaan semata. Ia milik publik.” (Pasal kunci dalam UU Penyiaran)
Payola di Mata Hukum Formal?
Menurut hukum, praktik payola bisa dikategorikan sebagai penyuapan atau gratifikasi, terutama sekali karena ia adalah "paid promote" yang tidak dilaporkan secara terbuka dan tidak ada mekanisme legal yang mengatur hubungan komersial tersebut.
Hal ini bisa dikenai pasal:
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU)
Di beberapa negara, payola dianggap sebagai kejahatan white-collar. Beberapa label dan radio di AS bahkan dikenai sanksi denda hingga jutaan dollar.
Sayangnya di Indonesia praktik ini jarang disorot secara hukum karena: tidak ada pelaporan formal, dikamuflase dengan narasi “kerjasama promosi”, para aktor yang terlibat bersifat lintas sektor, bahkan terhubung ke pejabat/konglomerat. Pelik, rumit, namun bukan berarti tidak bisa diurai.
Money politik bukan hanya terjadi di ranah politik praktis, di ranah politik gagasan juga ia berlangsung. Di industri musik? Ya lo tau lah. Politik uang dalam dunia bisnis dan perdagangan seringkali memuncak membentuk kartel. Kartel di industri musik? Ya lo tau lah, Bray. Feel it!
Harapan Tegaknya Hukum & Hadirnya Negara
Payola bukan sekadar urusan etik. Ia bisa menjadi bentuk nyata dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam ranah bisnis sekaligus ranah budaya. Payola bisa ditinjau dari sudut pandang hukum perdata maupun pidana.
Maka negara tak boleh (lagi) menutup mata. Kejaksaan, Kepolisian, KPK, KPPU, Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lembaga-lembaga etika media haruslah menjadi telinga dan mata yang tajam terhadap praktik-praktik pelanggaran seperti ini. Ini bukan sekadar soal musik, ini soal demokrasi budaya. Yang hendak kita bangun bersama adalah industri (musik) yang beradab.
Media vs Hak Publik, Transparansi Program Siaran
Radio, TV, DSP, medsos dan media penyiaran pubik lainnya bukan cuma sekadar saluran hiburan. Mereka adalah infrastruktur budaya. Maka ketika playlist ditentukan oleh "siapa yang bayar", bukan oleh kurasi obyektif, maka yang terjadi adalah pembajakan atas budaya. Lagu-lagu alternatif, pesan-pesan kritis, atau karya seni minoritas namun brilian akan terpinggirkan karena “gak punya jalur”. Sementara industri terus menjejalkan "hits instan" yang sebenarnya seringkali miskin arti dan makna.
Idealnya, setiap program siaran, termasuk playlist musik, harus transparan: Apakah disusun berdasarkan kurasi redaksi? Apakah merupakan konten berbayar? Siapa yang menentukan isi dan urutannya? Kalaupun lagu diputar karena berbayar, harusnya diumumkan secara jujur: “Lagu ini adalah konten bersponsor.” Sama seperti iklan. Tapi realitanya? Semua dibungkus rapi. Seolah-olah “pemirsa memilih”. Padahal dompetlah yang menentukan.
Soal kualitas karya, bagaimana suatu karya disebut layak booming, bagaimana mekanisme penentuan kelayakannya, siapa yang berhak menentukan? Kriterianya? Akan diulas di tulisan berikutnya. Tema "pengkurasian/penjurian" musik akan kita bahas tuntas pada tulisan terpisah setelah ini.
Payola bukan sekadar aib di balik layar. Ia adalah cermin ketidakmerataan kesempatan dan ketimpangan struktural dalam industri musik. Dan selama tak ada penindakan serius, praktik komodifikasi budaya oleh kekuatan modal akan terus berjalan, menghapus keberagaman, membungkam ekspresi alternatif, dan menyesatkan (selera) publik.
Harapan pada Jurnalisme yang Obyektif, Editorial & Kuratorial yang Jujur
Media punya tanggung jawab lebih dari sekadar klik dan trending. Mereka juga punya kewajiban etik untuk menghadirkan kurasi yang sehat, adil, dan merdeka dari tekanan apapun, termasuk suruhan do it karena duit.
Harapan pada Audiens yang Cerdas dan Bermartabat
Penonton, pendengar, followers, dan kita semua sesungguhnya punya kuasa. Kuasa atas "jempol" kita sendiri. Tombol skip, tombol follow/unfollow, tombol share, komen, dan report, itu semua adalah bentuk instrumen suara "politik" kita. Lebih jauh dari sekadar politik kepartaian, ini adalah politik kesadaran. Kesadaran untuk menyimak yang tersembunyi, mendukung yang terpinggirkan, merayakan keberagaman tanpa terdistraksi dan terhipnotis segala hal yang palsu dan semu.
Masa Depan Musik Yang Cerah & Peran Komunitas Musisi Mandiri
“Lalu, kita harus bagaimana?” pertanyaan getir sering bermunculan di tengah sesaknya ruang musik yang dipenuhi aroma manipulasi--modal.
Yang kita butuhkan bukan sekadar semangat untuk bangkit terus menerus, tapi gerak bersama yang terarah. Meski senyap, sebenarnya ada dan sudah banyak benih harapan yang tumbuh. Kini saatnya mereka terus dirawat, disiram dan dijaga, agar kelak bisa menjadi hutan lebat yang menandingi gurun ketimpangan
Jangan tunggu panggung diberikan. Buat panggung sendiri. Jangan menunggu diundang. Ciptakan ekosistem sendiri. Komunitas bukan cuma kumpulan seniman, ia bisa juga dijadikan laboratorium ide, rumah eksistensi dan resistensi, serta tempat bertumbuh secara waras dan sehat tanpa terkooptasi industri besar.
Tapi kita bisa apa?
Kita bisa ngomong, suarakan. Lewat tulisan, lagu, video, diskusi publik, podcast, karya seni, apa saja. Jangan diam. Diam hanya menyuburkan budaya tak adil yang sudah menahun menggerogoti akar ekosistem musik kita. Kita bisa bikin karya. Tetap berkarya adalah bentuk perlawanan. Setiap lagu dan pemasarannya yang jujur adalah bukti bahwa kita belum menyerah. Bahwa musik masih hidup bukan karena modal, tapi karena makna.
Kita bisa laporkan kalau ada indikasi suap (payola), penyelewengan, pelanggaran hukum. Catat, dokumentasikan, dan laporkan. Perkarakan. Gunakan jalur yang tersedia: KPPU, KPI, Kominfo, Ombudsman, hingga platform jurnalisme warga. Perlawanan memang terkadang sunyi, tapi bukan berarti sia-sia.
Kita bisa melawan, namun bukan berarti anarkis ya. Tapi aktif: bertanya, menolak tunduk, mendobrak narasi palsu, dan membangun ruang baru. Lawan dengan kesadaran, ketulusan, dengan strategi, dengan kolaborasi.
“Kita bukan anti-populer. Kita cuma pengen yang populer itu adil.”
Bukan berarti musisi mandiri membenci popularitas. Justru, banyak dari kita inginnya musik sampai ke telinga banyak orang karena memang layak, bukan karena lewat jalan tikus gelap yang penuh sogokan. Kita ingin popularitas yang sehat, adil, dan terbuka untuk siapapun yang layak, bukan hanya dia-dia aja yang ‘berkantong tebal’.
Angkat karya teman. Jangan saling sikut. Karena musuh kita bukanlah sesama pejuang budaya atau sesama pemusik, tapi sistem yang selama ini jelas tak adil pada semuanya.
TESTIMONIA
[Eks Penyiar Radio Swasta, 2023]: “Suara yang didengerin itu suara yang disponsori. Titik.”
[Manajer Band Rock Alternatif, diskusi soal chart digital, 2024]: “Kita tuh bisa viral bukan karena didengerin, tapi karena dilolosin.”
[Penyiar Radio, 2023]: “Kadang kita juga frustrasi. Yang punya duit, dia yang diputer. Yang bagus? Nggak selalu dapet giliran.”
[Pengamat Media, 2024]: “Industri ini bukan soal siapa yang paling layak, tapi siapa yang paling deket sama pintu kekuasaan.”
[Produser Acara Musik TV, 2021]: “Kami punya slot terbatas. Kalau semua minta keadilan, siapa yang bayar operasional kami?”
[Seniman Lintas Disiplin, 2025]: “Kita sering ditanya: ‘kenapa seni nggak relevan?’ Padahal yang nggak relevan itu kurator industrinya.”
[Beatmaker Muda, Jakarta, 2023]: “Gue awalnya pikir payola itu mitos. Tapi pas temen gue cerita harganya bisa sampe puluhan juta buat satu lagu, gue speechless.”
[Jurnalis Musik Lepas, Yogyakarta, 2022]: “Ada label besar di Indo yang terang-terangan bilang: ‘Amplop itu bagian dari strategi distribusi kami."
[Kurator Festival Musik Independen, 2023]: “Payola itu ibarat narkoba di industri musik. Semua orang tahu, tapi pura-pura nggak tahu.”
[Label Kecil, 2023]: “Dulu gue pikir ‘payola’ itu mitos. Ternyata itu SOP yang nggak tertulis tapi dijalankan semua orang.”
[Pemerhati Hukum Musik, 2024]: “Payola modern nggak selalu berbentuk uang tunai. Kadang barter, kadang jabatan, kadang kuasa sosial.”
[Podcaster Musik, 2025]: “Episode soal ‘bayar-bayar agar bisa viral’ adalah yang paling banyak DM curhatnya. Ternyata semua ngalamin.”
[Musisi R&B, 2023]: “Playlist Spotify lokal pun sekarang banyak yang ‘berbayar di balik layar’. Ada harga buat ‘rekomendasi’.”
[Sound Engineer Panggung, 2022]: “Bahkan live performance bisa diatur. Lo bayar EO tertentu, tiba-tiba lo jadi opening act artis gede.”
[Digital Distributor, 2024]: “Playlist editorial itu bisa didorong lewat agency tertentu, tapi nggak gratis.”
[Pendengar Umum, 2025]: “Aku sering ngerasa suara kami sebagai pendengar itu nggak dihitung. Playlist editorial DSP kayak udah diset dari langit.”
[MC Event Musik, 2025]: “Kalau lo mau tampil di festival A, harus ‘kenalan’ dulu. Dan kenalan di sini artinya: kenalan sama nominal.”
[Staf Manajemen Artis, 2023]: “Kita pernah dikasih rate card ‘non-official’ dari satu media. Tiap harga beda slot, beda exposure.”
[Anak Gen Z, 2025]: “Kami pikir TikTok itu natural. Tapi ternyata banyak banget konten musik itu disetting dari awal.”
[Staf Label Mayor, 2022]: “Lo bisa beli tempat di rak depan toko, bisa beli urutan trending YouTube, bisa beli fans juga.”
[Dosen Komunikasi, 2023]: “Ekosistem ini bukan cuma media konvensional. Bahkan konten kreator independen pun bisa masuk skema payola.”
[Pekerja Event Musik, 2024]: “Venue punya list siapa aja yang ‘boleh’ tampil, dan itu bisa diubah dengan transfer dana.”
[Kreator Musik Indie, 2025]: “Kadang musuh kita bukan kualitas, tapi kuasa promosi yang dibalut kata ‘algoritma’.”
[Music Content Strategist, 2023]: “Buat gue, iklan musik itu fair kalo transparan. Tapi kalau embel-embel ‘editorial choice’ tapi ternyata bayar? Nah itu penipuan.”
[Musisi Folk, 2022]: “Label besar bisa punya budget marketing kayak brand mobil. Kita? Cuma bisa doa sama jago medsos.”
[Eks Pengelola Kanal YouTube Musik, 2023]: “Masalahnya bukan di promosi, tapi di ilusi. Kita disuruh percaya semua itu ‘organik’.”
[Pengamat Skena Lokal, 2024]: “Selama yang diuntungkan tetap bisa mengatur arus, yang tersingkir nggak akan pernah dikasih perahu.”
[Koordinator Komunitas Musik Daerah, 2023]: “Ada band jazz keren dari Makassar. Nggak ada yang dengerin, padahal kualitasnya bisa masuk festival internasional. Cuma karena nggak punya link promosi.”
[Solois Perempuan, 2022]: “Gue pribadi sempat mikir berhenti bikin musik karena rasanya selalu kalah sebelum mulai.”
[Pengiklan Produk, 2023]: “Gue nggak masalah pasang iklan lagu asal transparan. Tapi jangan nyamar jadi opini netral.”
[Musisi Senior, 2024]: “Zaman dulu pun promosi udah keras. Tapi dulu jujur. Sekarang mah penuh kamuflase.”
[Pakar Marketing Musik, 2025]: “Perlu dibedakan: iklan sehat itu ngajak. Iklan jahat itu nyuap ekosistem.”
[Fans Loyal, 2022]: “Gue jadi ragu suka lagu itu karena lagunya enak, atau karena terlalu sering ‘dipaksa’ denger.”
[Penyusun Kurikulum Musik, 2024]: “Etika periklanan musik jarang diajarin. Padahal efeknya besar ke generasi penerima musik.”
[YouTuber Musik, 2023]: “Gue pernah tolak sponsor lagu karena mereka nyuruh gue bilang itu ‘bukan sponsor’. Lah, ngibul dong?”
[Seniman Teater, 2025]: “Musik udah jadi komoditas kayak sabun. Diiklankan, dijual, ditinggalkan.”
[Rapper muda, 2023]: “Lagu gue masuk nominasi tapi nggak diputer. Padahal yang menang malah kayak hasil lomba lipsync.”
[Manajer Musisi Independen, 2024]: “Musisi mandiri itu kayak jualan di pinggir jalan yang nggak boleh masuk mal.”
[Musisi Elektronik, 2024]: “Kualitas udah oke. Tapi kualitas nggak bisa bayar slot promo.”
[Vokalis Band Punk, 2024]: “Kita nggak miskin kualitas, cuma nggak mampu nyewa pintu-pintu distribusi.”
[Radio Programmer, 2023]: “Banyak lagu bagus dari daerah nggak pernah masuk radar. Soalnya nggak ada dana buat dorong ke pusat.”
[Analis Industri Kreatif, 2022]: “Payola menyingkirkan talenta yang nggak punya modal. Tapi sayangnya itu dianggap normal.”
[Musisi dari Papua, 2025]: “Kalau kamu bukan dari Jakarta, dan bukan dari label gede, siap-siap jadi suara yang diredam.”
[Kru Festival Musik, 2023]: “Banyak talenta muda batal tampil gara-gara slot mereka diganti sama artis titipan sponsor.”
[Seniman Tradisional, 2024]: “Yang punya budaya kaya, justru sering nggak punya akses. Yang akses luas, kadang malah pinjam budaya.”
[Guru Seni SMA, 2025]: “Anak-anak berbakat saya malah minder karena lihat yang naik daun itu yang ‘berduit."
[Pekerja Agensi Musik, 2023]: “Lucunya, yang curang pun merasa wajar karena semua orang juga curang.”
[Pendengar Aktif, 2022]: “Gue denger lagu receh diputer terus. Terus pas gue protes, kata orang: ‘Ya emang gitu sekarang. Biasa aja, Bro.’”
[Musisi Veteran, 2023]: “Gue nggak marah lagi. Cuma udah capek berharap.”
[Solois Indie, 2023]: “Amplop itu bukan sekadar uang. Tapi relasi. Tanpa itu, lo kayak teriak di gua.”
[Penulis Lagu, 2024]: “Gue bikin lagu yang bikin orang nangis, tapi tetep nggak ‘dilirik’ karena nggak bawa sponsor.”
[Manajer Indie Label, 2025]: “Kalau lo nggak bisa bayar campaign digital, lo bakal dikubur sama algoritma.”
[Band Rock Lokal, 2022]: “Kami nggak bisa ‘bakar duit’ kayak yang lain. Jadi ya, tetep di pinggiran.”
[Pembuat Video Musik, 2023]: “Video klip gue dibilang bagus, tapi nggak masuk playlist karena ‘kurang dana marketing’.”
[Remaja Pendengar Musik, 2024]: “Kadang lagu yang bikin aku jatuh cinta tuh bukan yang viral. Tapi yang nyempil dan jujur.”
[Produser Indie, 2025]: “Payola membunuh harapan banyak orang kreatif yang nggak lahir dengan privilege."
[Aktivis Musik, 2023]: “Banyak orang bilang ‘ya emang gitu dunia musik’. Padahal itu tanda kita udah mati rasa.”
[Dosen Sosiologi, 2025]: “Kalau generasi baru disuguhi sistem rusak terus-menerus, mereka akan menganggap rusak itu wajar.”
[Komposer, 2023]: “Yang bikin frustrasi bukan cuma sistemnya. Tapi karena semua diem, pura-pura nggak tau.”
[Pekerja Label, 2022]:“Gue pernah nolak sistem payola. Akhirnya gue out. Teman-teman bilang: ‘lo aja yang idealis’.”
[Pemerhati Budaya Pop, 2025]: “Pasar kita udah kebal terhadap ketimpangan. Ini krisis rasa.”
[Anak Magang Radio, 2024]: “Kita belajar cara menyuap duluan sebelum belajar cara memutar musik.”
[Aktivis HAM Digital dan Budaya, 2024]: “Kalau payola itu ilegal, kenapa belum ada satupun yang dipenjara?”
[Jurnalis Hukum Dunia Entertainment, 2023]: “Di luar negeri payola bisa bikin label kena denda miliaran. Di sini? Dijadikan SOP.”
[Akademisi Seni dan Media, 2022]:“Ini bukan sekadar etika industri, ini soal keadilan publik. Musik itu bagian dari hak budaya.”
[Dosen Komunikasi]: "Ini semua soal kuasa suara. Yang punya alat paling keras, suaranya paling didengar."
[Pengacara HAM, 2023]: “Bentuk payola tertentu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi dan masuk ranah pidana.”
[Aktivis Antikorupsi, 2024]: “Korupsi bukan cuma soal proyek negara. Musik juga bisa jadi ladang kotor yang sama.”
[Awak KPI, 2022]: “Kami menerima aduan tentang transaksi gelap dalam tayangan musik. Tapi buktinya sulit.”
[Etikawan Media, 2023]: “Setiap konten yang disamarkan sebagai ‘organik’, padahal iklan, melanggar etika jurnalistik.”
[Wartawan Investigasi, 2024]: “Payola itu industri hitam yang susah dilacak, karena semua pihak saling jaga rahasia.”
[Mahasiswa Hukum, 2025]: “Gue jadi pengen skripsi tentang regulasi payola di era digital. Ini belum disentuh serius.”
[Lembaga Perlindungan Konsumen, 2025]: “Kalau konsumen nggak diberi tahu mana konten iklan dan mana konten murni, itu pelanggaran hak.”
[Songwriter Wanita, 2023]: “Gue percaya, selalu ada cara jujur buat nyampe ke hati orang. Tapi emang jalannya lebih panjang.”
[Pemuda Komunitas Musik Minoritas, 2024]: “Masa depan musik kita ada di tangan yang berani bilang ‘nggak’ ke sistem korup.”
[Anak SMA, 2024]: “Kami pengen denger musik yang jujur. Nggak masalah nggak viral, asal real.”
[Musisi DIY, 2023]: “Gue percaya jalan independen masih mungkin. Tapi perlu komunitas, bukan kompetisi.”
[Aktivis Kultural, 2025]: “Kalau kita berhenti ngomongin soal ini, sistem bakal makin ganas.”
[Kolektif Musik Daerah, 2024]: “Sekarang bukan cuma bikin lagu. Tapi juga bikin ruang distribusi alternatif.”
[Programmer Platform Musik Lokal, 2025]: “Kami sedang coba bikin algoritma yang lebih adil. Meskipun kecil, itu langkah.”
[Peneliti Budaya, 2024]: “Kesadaran kolektif adalah satu-satunya vaksin melawan industri yang menindas.”
[Musisi Perempuan, 2025]: “Kita bisa mulai dari nol lagi. Bikin sistem kecil, bersih, lalu bareng-bareng perbesar.”
[Anggota Kolektif Musik, 2023]: “Gue pilih jujur dan konsisten. Nggak cepet naik, tapi gue tenang tidur.”
[Penggiat Komunitas, 2024]: “Bersuara itu penting. Tapi jangan lupa, berkarya juga bentuk perlawanan.”
[Jurnalis Muda, 2022]: “Satu artikel jujur bisa lebih bergema dari ribuan konten berbayar.”
[Pendidik Seni, 2023]: “Ajari anak-anak soal etika sejak awal. Biar mereka tumbuh nggak ikut sistem rusak.”
[MC Underground, 2025]: “Kita bukan anti-populer. Kita cuma pengen yang populer itu adil.”
[Mahasiswa Seni Pertunjukan, 2022]: “Gue tahu ini berat. Tapi kalau kita diem semua, yang berkuasa ya makin semena-mena.”
[Pendengar Militan, 2025]: “Aku unfollow semua akun musik palsu. Aku pilih dengerin yang jujur aja.”




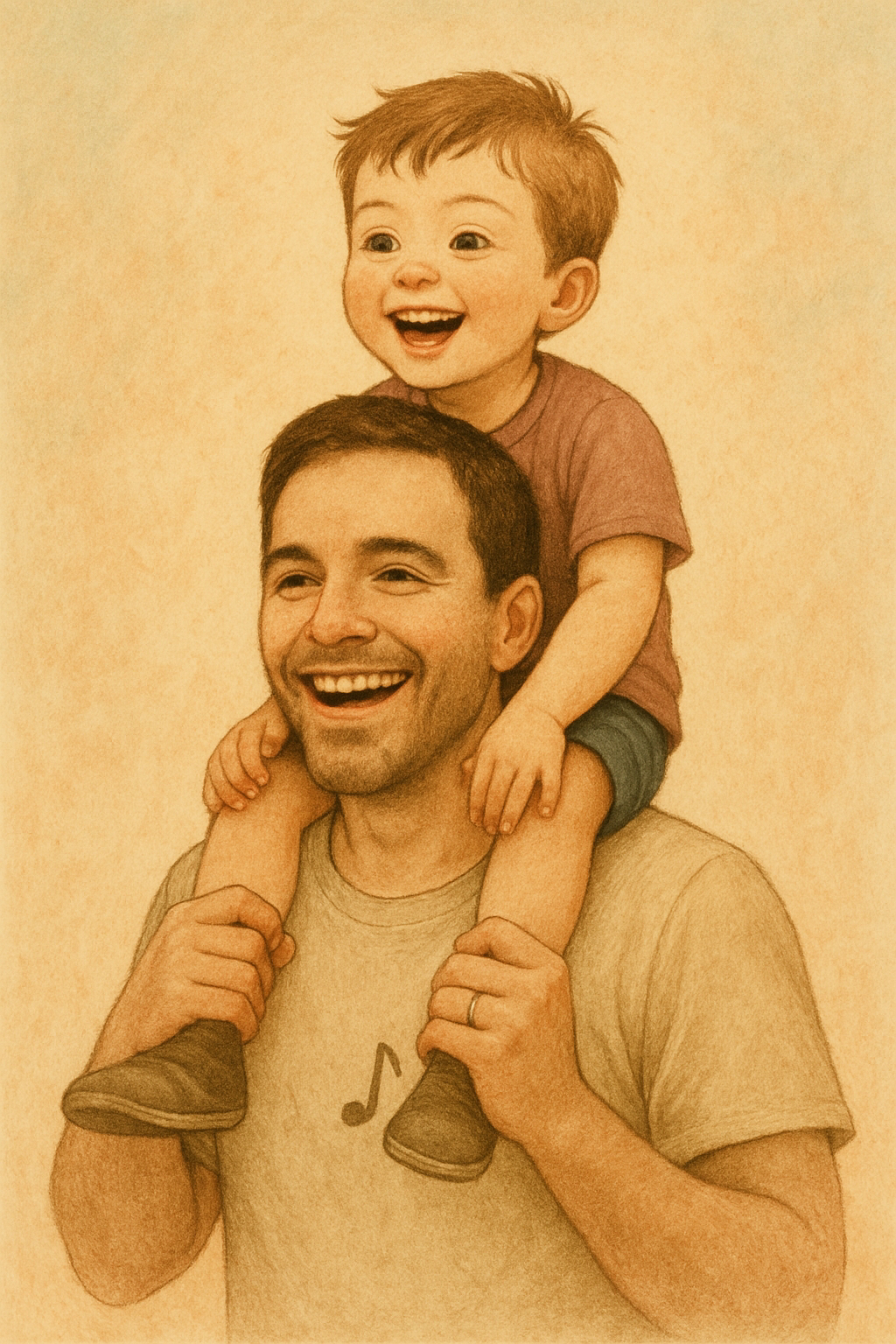











Tidak ada komentar:
Posting Komentar